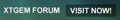
Oleh: Akmal Syafril
Eksploitasi media massa terhadap kasus Ahmadiyah dewasa ini seolah hendak mengidentikkan dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang menghendaki pemisahan antara Ahmadiyah dan umat Muslim, dan kelompok yang ingin menghancurkan Ahmadiyah secara frontal dan fisikal. Kelompok pro-Ahmadiyah selalu menunjuk pihak-pihak seperti FPI yang memang selalu bersikap frontal, sehingga nampak seolah-olah semua yang kontra dengan Ahmadiyah bersikap demikian. Kenyataannya, mayoritas umat Islam dunia menolak Ahmadiyah namun tidak melakukan tindak kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah maupun aset-asetnya. PKS, FUI, DDII, dan Tim Pembela Muslim (TPM) hanyalah sebagian saja yang mengambil langkah elegan untuk menolak Ahmadiyah. Sayang, media massa yang jauh dari objektif nampaknya luput mencermati fenomena ini.
Sebagian pihak pro-Ahmadiyah dengan entengnya menggunakan ayat berikut sebagai dalil; “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 256)
Eksploitasi ayat secara tidak bertanggung jawab seperti ini justru menunjukkan bahwa pelakunya memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu Al-Quran. Pada prinsipnya, ayat-ayat Al-Quran memang bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang, asalkan tidak menyelisihi As-Sunnah. Sebagai contoh, jika ingin mengaplikasikan ajaran zuhud sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, tidak boleh dengan cara menyiksa diri, karena yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah saw. Demikian juga ayat lakum diinukum wa liyadiin tidak bisa dijadikan pembenaran untuk paham pluralisme dan sinkretisme, karena Rasulullah saw. tidak pernah membenarkan tindakan yang demikian. Dengan kata lain, penafsiran Al-Quran dibatasi oleh suri tauladan yang telah diberikan oleh pribadi Qur’ani terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu Rasulullah saw.
Jika kita mencermati Sirah Nabawiyah, maka ayat Laa ikraaha fid-diin di atas tidaklah tepat untuk digunakan dalam kasus Ahmadiyah yang telah sesat dari ajaran Islam yang lurus. Meskipun Rasulullah saw. sangat menghormati agama-agama lain dan tak pernah mengganggu rumah-rumah ibadah mereka, namun sejarah juga mencatat sikap beliau yang sangat keras terhadap ‘berhala-berhala’ di Mekah dan Masjid Dhirar. Tradisi penyembahan berhala di Mekah adalah penyimpangan yang nyata dari millah Nabi Ibrahim as., sedangkan Masjid Dhirar adalah masjid yang didirikan dengan niat yang buruk. Untuk kedua kasus penyimpangan ini, Rasulullah saw. tidak ragu-ragu untuk menghapuskannya secara total. Dengan kata lain, beliau bersikap toleran terhadap umat beragama lain, namun tegas terhadap mereka yang menyimpang dari ajaran Islam.
Kita tidak bisa mengharapkan manusia lain yang lebih Qur’ani daripada Rasulullah saw. Oleh karena itu, sikap beliau yang keras terhadap penyimpangan agama tersebut harus dijadikan konsideran dalam menafsirkan ayat Laa ikraaha fid-diin. Meskipun penafsiran ayat ini tidak tuntas sampai di sini, namun jelaslah bahwa ayat tersebut tak bisa dijadikan dalil untuk membenarkan eksistensi sebuah aliran yang menikung tajam dari aqidah yang lurus.
Masalah utamanya adalah pada status Ahmadiyah itu sendiri. Jika mereka mau menyebut dirinya sebagai umat Non-Muslim, maka masalah bisa dianggap selesai. Mereka akan dinyatakan sebagai umat agama lain dengan segala konsekuensinya, termasuk dalam hukum waris, nikah, sosial, politik, dan juga akan dinyatakan terlarang memasuki Tanah Suci Mekah. Selebihnya, takkan ada masalah. Namun jika menyatakan diri sebagai umat Muslim, maka ada beberapa batasan yang tak mungkin dilanggar. Sayangnya, batasan tersebut telah dilanggar sejak jauh-jauh hari oleh Ghulam Ahmad al-Kadzdzab.
Figur Ghulam Ahmad merupakan masalah sentral yang lain lagi. Sebagian menyebutnya sebagai nabi, sebagian lagi (baik untuk alasan taktis-strategis ataupun alasan lainnya) menyebutnya sebagai pembaharu. Menyebutnya sebagai nabi tentu menimbulkan masalah, karena Rasulullah saw. telah beberapa kali menegaskan : laa nabiyya ba’diy (tak ada Nabi sesudahku). Mengakui Ghulam Ahmad sebagai nabi sama saja dengan menuduh Rasulullah saw. sebagai pembohong.
Kepribadian Ghulam Ahmad sendiri memang banyak mengundang pertanyaan, apalagi karena ia mengklaim dirinya sendiri sebagai nabi. Mulai dari sikapnya yang anti-Jihad dan terlalu ‘penurut’ terhadap pemerintah kolonial Inggris, sikapnya yang memalukan ketika memaksa seorang lelaki untuk menikahkannya dengan anak perempuannya, dan klaim-klaimnya yang tak terbukti, antara lain klaim bahwa rumahnya takkan dimasuki penyakit kolera (padahal ia sendiri kemudian meninggal karena kolera). Baik di negeri asalnya maupun di Indonesia, Ahmadiyah memberikan jaminan surga bagi mereka yang membeli ‘kapling makam’ di suatu tempat yang dinyatakan suci. Permainan uang milik jamaah memang bukan barang baru, baik bagi Ghulam Ahmad maupun para penerusnya. Dari sini, kita pun pantas bersikap kritis : pembaharuan macam apa yang telah dipelopori oleh Ghulam Ahmad sesungguhnya?
Dengan reputasi yang berantakan seperti ini, Ghulam Ahmad jauh dari pantas untuk diakui sebagai pembaharu, apalagi nabi. Oleh karena itu, jika ingin diakui sebagai bagian dari umat Muslim, maka tidak cukup bagi jamaah Ahmadiyah untuk menyebut Ghula Ahmad sebagai pembaharu (bukan nabi), namun juga wajib menolak untuk mengikutinya, bahkan sebagai pembaharu sekalipun. Jika itu terjadi, tentu saja, eksistensi Ahmadiyah menjadi tak berarti lagi, karena ia tak mungkin dipisahkan dari figur pendirinya. Dengan kata lain, hanya ada dua pilihan bagi Ahmadiyah, yaitu (1) membubarkan diri, atau (2) memisahkan diri sepenuhnya dari umat Muslim.
Di luar hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan pribadi Ghulam Ahmad, ada pula masalah-masalah lain yang menghambat integrasi Ahmadiyah dengan umat Muslim sedunia. Media massa sangat berkepentingan untuk menyebarkan kesan seolah-olah umat Islam-lah yang telah mengucilkan Ahmadiyah, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.
Di mana-mana kita melihat jamaah Ahmadiyah membangun desa-desa sendiri secara tertutup. Mereka membuat masjid-masjidnya sendiri dan tak merasa perlu berinteraksi secara wajar dengan umat Muslim lainnya. Ghulam Ahmad sendiri sudah menegaskan bahwa para pengikutnya diharamkan untuk shalat di belakang non-Ahmadi. Justru Ahmadiyah-lah yang sudah sejak lama memberi cap kafir kepada orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Bedakan dengan MUI dan organisasi ulama lainnya yang hanya memberi vonis sesat pada ajaran Ahmadiyah, dan bukan pada pribadi pengikut-pengikutnya.
Soal provokasi dan tindak kekerasan, Ahmadiyah adalah jagonya. Ghulam Ahmad mengklaim dirinya berjasa terhadap pemerintah Inggris karena telah mengirimkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk mendukung Inggris dalam menaklukkan Iraq dahulu. Ghulam Ahmad juga melarang pengikut-pengikutnya untuk menshalatkan jenazah umat Muslim, sebagaimana mereka tak boleh menshalatkan orang-orang Hindu dan Nasrani. Ghulam Ahmad mengklaim dirinya lebih utama daripada al-Hasan ra. dan al-Husain ra., bahkan merendahkan Abu Bakar ra. dan ‘Umar bin Khattab ra. Bahkan dengan ‘keberanian’ yang amat mengherankan, ia pun mengklaim dirinya lebih utama daripada Nabi ‘Adam as., Nabi Nuh as., dan Nabi ‘Isa as.
Hal-hal semacam ini telah tuntas dibahas oleh alm. Syaikh Ihsan Ilahi Zhahir dalam salah satu bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengapa Ahmadiyah Dilarang?
Maka, melihat masalah Ahmadiyah dari kaca mata ‘kebebasan berpendapat’, ‘kebebasan berkeyakinan’ dan semacamnya masih jauh dari memadai. Ghulam Ahmad al-Kadzdzab dan aliran yang didirikannya telah bermasalah sejak awal, dan tak mungkin mendamaikannya dengan ajaran Islam yang lurus. Tidaklah realistis mengharapkan jamaah Ahmadiyah mampu bertindak lurus sementara mereka berdiri di atas pondasi ajaran yang jelas-jelas menyimpang.
Tidak mungkin ada pengikut ajaran Hitler yang mampu memimpin dengan kasih sayang, sebagaimana tidak mungkin ada pengikut Ahmadiyah yang bisa menjalankan ajaran Islam dengan baik. Ajaran Ahmadiyah memang bermasalah dari akarnya, dan dengan sendirinya, kalau mau mengikuti ajaran Ghulam Ahmad, sudah barang tentu menyimpang dari ajaran Islam yang lurus.
Penulis adalah mahasiswa S2 Jurusan Pemikiran Islam Universitas Ibnu Khaldun"